Menyelami Batin Seorang Gubernur, Menjadi Pemimpin dalam Keheningan Jiwa

Saat malam telah lengang dan suara angin dari arah Gunung Klabat berbisik pelan di sela-sela dedaunan, aku duduk sendiri di ruang kerja, lampu redup menyinari meja tempat berkas-berkas usulan jabatan tertumpuk. Satu per satu nama tertulis di sana—beberapa kubaca cepat, beberapa kupandangi lama.
“Siapakah yang pantas? Siapa yang sekadar dekat? Siapa yang diam-diam mengirim isyarat loyalitas dengan harapan jabatan? Dan siapa yang sungguh-sungguh berniat mengabdi untuk rakyat?” pikirku dalam diam.
Aku paham benar bahwa di balik setiap keputusan yang kuambil, nasib ribuan—bahkan jutaan—orang bisa berubah. Salah menempatkan satu orang, rusaklah satu sistem. Salah mengangkat karena rasa sungkan, padamlah harapan rakyat kecil yang hanya berharap hidupnya sedikit lebih layak.
Aku teringat petuah leluhur kami, “Si tou timou tumou tou”—manusia hidup untuk memanusiakan manusia. Bukan untuk memperalatnya, bukan untuk menyuapnya dengan jabatan. Nilai itu bukan sekadar semboyan di dinding ruang kerja, tapi harus hidup dalam setiap langkah kepemimpinan ini.
Kedekatan? Aku manusia juga. Kadang ada rasa tak enak ketika yang datang adalah teman seperjuangan, saudara seiman, atau mereka yang dulu setia dalam sunyi perjuangan. Tapi ini bukan perkara pribadi. Ini soal amanat.
“Nerimo ing pandum,” kata bijak dari tanah Jawa, mengajarkanku untuk ikhlas menerima dan tidak serakah dalam menggunakan kuasa. Tapi ikhlas tak berarti pasrah pada sistem yang rusak. Aku tak bisa membiarkan jual beli jabatan menjadi budaya yang menular hingga ke akar-akar pemerintahan.
Di sisi lain, filosofi Toraja menampar kesadaranku dengan halus:
“Aluk Todolo” menekankan keseimbangan antara kehidupan dunia dan nilai spiritual. Bahwa jabatan bukan sekadar alat duniawi, tetapi titipan ilahi yang harus dijalankan dengan tanggung jawab dan hormat. Di mana setiap langkah harus selaras dengan langit dan bumi.
Malam ini, aku menutup mata dan berdoa, bukan minta kemudahan, tapi hikmat.
“Tuhan, beri aku mata untuk melihat bukan hanya apa yang terlihat, tapi yang tersembunyi di balik sikap manusia. Beri aku hati yang tidak mudah goyah karena tekanan, dan beri aku keberanian untuk memilih yang benar meski tak populer.”
Kurasakan suara-suara rakyat di kepalaku:
“Pak Gub, kami butuh jalan yang baik.”
“Kami butuh dokter di puskesmas.”
“Kami butuh guru yang benar-benar mau mengajar.”
“Kami butuh keadilan, bukan kedekatan!”
Maka kuputuskan, mereka yang akan kupilih menduduki posisi penting adalah mereka yang tidak memandang dari mana ia berasal, siapa orang tuanya, atau seberapa keras ia berteriak dalam kampanye. Yang kutanya hanyalah: Apakah ia mampu? Apakah ia mau melayani? Apakah ia mencintai rakyat Sulawesi Utara sepenuh hatinya?
Karena jabatan adalah sarung pedang, bukan mahkota. Ia bisa melukai jika digenggam sembarangan, tapi bisa melindungi jika digunakan oleh tangan yang tepat.
Dan aku memilih…
Untuk menolak suap yang dibungkus hadiah.
Untuk menyisihkan loyalitas buta yang tak berbuah karya.
Untuk mengangkat orang-orang bercahaya karena kerja dan karakter, bukan sorot popularitas.
Malam makin larut. Namun tekadku justru semakin terang.
Karena kepemimpinan bukan tentang aku, tapi tentang mereka yang tak pernah masuk ruang ini, tapi menggantungkan harapannya pada kebijakan yang akan kutanda tangani esok pagi.
“Menjadi pemimpin itu bukan soal berkuasa atas orang lain, tapi berani menanggung beban keputusan dengan penuh kesadaran dan cinta pada rakyat.”
Itulah batin seorang Gubernur.
Itulah arah kepemimpinan Sulawesi Utara.
Yang memihak pada kebenaran.
Yang melangkah dalam hikmat.
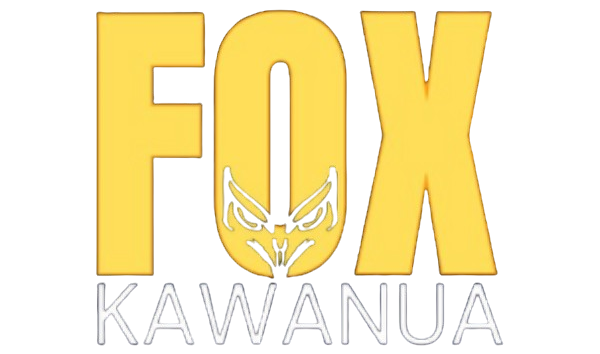





Tidak ada komentar